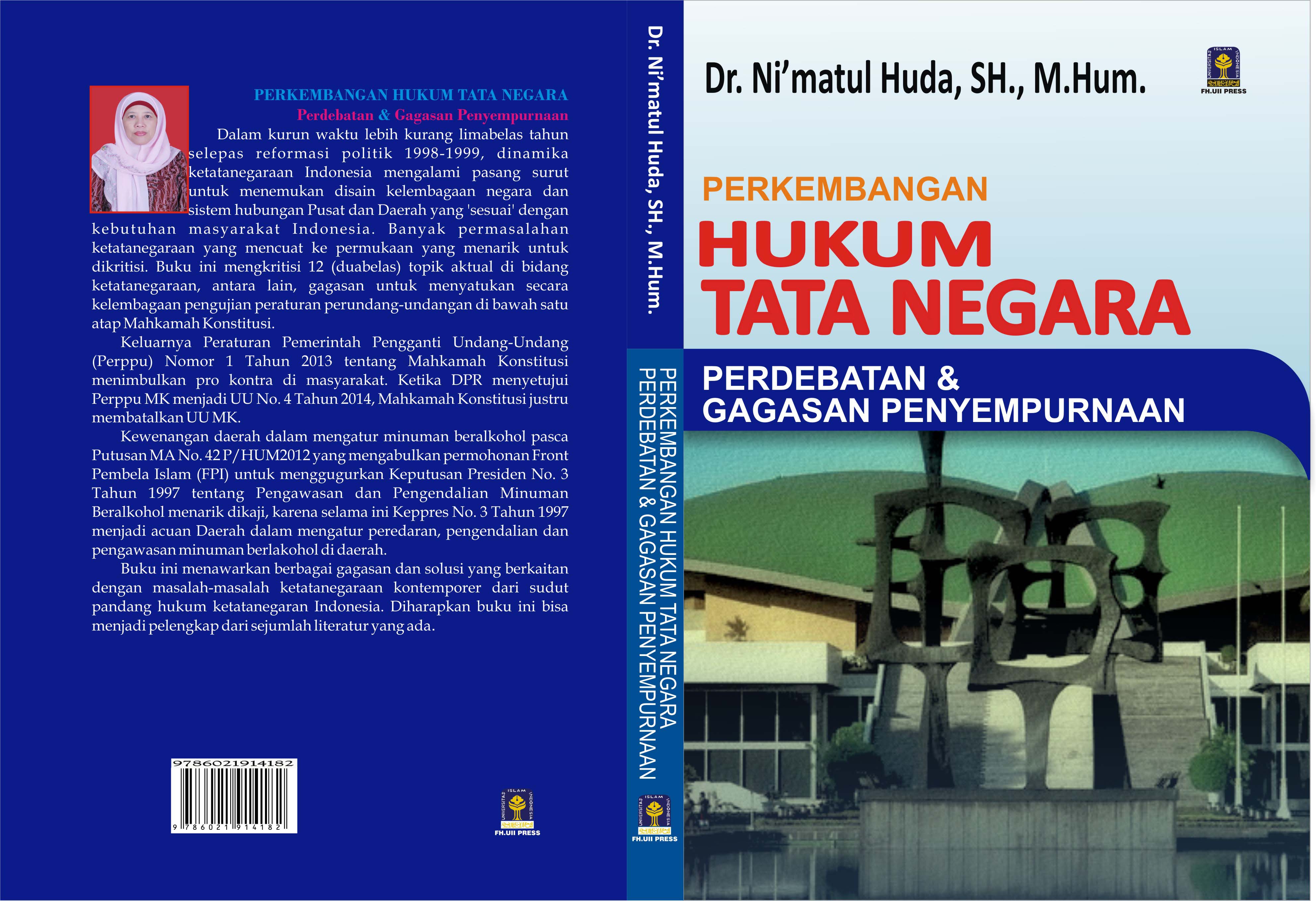Absennya Djarot di Pelantikan Gubernur DKI
Jamaludin Ghafur, SH., MH[1]
Salah satu yang disoroti publik di tengah gegap gempitanya perayaan pelantikan gubernur/wakil gubernur baru DKI Jakarta adalah ketidakhadiran mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat. Pendapat publik terbelah menjadi dua: menyalahkan dan membenarkan. Pendapat pertama menganggap hal itu sebagai sikap yang tidak etis dan bukan merupakan sikap seorang negarawan. Terlebih absennya Djarot karena sedang berlibur. Sementara mereka yang tidak mempersoalkan, berargumen bahwa secara hokum memang tidak ada kewajiban, terlebih serah terima jabatan (sertijab) sudah diwakili oleh Sekda DKI Saefullah sebagai pelaksana harian (Plh).
Masa Jabatan Gubernur
Salah satu alasan yang dikemukakan Djarot atas ketidakhadirannya dalam pelantikan tersebut karena menganggap bahwa dirinya per hari minggu (15/10) masa jabatannya sudah berakhir dan telah ditunjuk Plh untuk melaksanakan tugas gubernur. Artinya, sejak hari minggu sampai dilantiknya gubernur yang baru, terjadi kekosongan jabatan gubernur DKI Jakarta sehingga diperlukan Plh untuk mengisi jabatan tersebut.
Hal ini tentu sangat disayangkan karena desain pengaturan tentang masa jabatan gubernur tidak rancang sedemikian rupa agar terjadi kesinambungan antara kepemimpinan sebelumnya ke kepemimpinan berikutnya. Semestinya hokum mengatur bahwa masa jabatan Gubernur yang lama akan berakhir tepat pada saat dilantiknya Gubernur yang baru. Dengan cara seperti ini, ke depan diharapkan tidak akan ada lagi insiden di mana mantan gubernur tidak menghadiri sertijab dan pelantikan gubernur yang baru.
Di lembaga kepresiden, kontinyuitas masa jabatan kepemimpinan ini sudah terjadi karena masa jabatan Presiden yang lama akan berakhir tepat pada saat presiden yang baru dilantik dan disumpah. Sehingga dengan desain pengaturan seperti ini, dapat dipastikan tidak akan terjadi kekosongan kepemimpinan yang memerlukan Plh.
Konvensi Ketatanegaraan
Dari sudut peraturan perundang-undanag, memang tidak ada keharusan bagi gubernur lama untuk menghadiri pelantikan gubernur yang baru. Namun demikian, kebiasaan selama ini menunjukkan bahwa seluruh gubernur lama selalu hadir dalam pelantikan gubernur baru. Kebiasaan ini dapat dikategorikan sebagai konvensi ketatanegaraan (constitutional conventions) yang dalam perspektif hokum tata negara (HTN), konvensi merupakan salah satu sumber hokum tata negara. Oleh karenanya, konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan semacam itu juga dianggap harus ditaati sebagai konstitusi, yaitu dalam makna konstitusi yang tidak tertulis. Konvensi/kebiasaan ketatanegaraan sekalipun sifatnya tidak tertulis, namun dianggap baik dan berguna dalam penyelenggaraan negara menurut undang-undang dasar. Oleh karena itu, meskipun tidak didasarkan atas ketentuan konstitusi tertulis, hal itu tetap dinilai penting secara konstitusional (constitutionally meaningful) (Jimly Asshiddiqie: 2006, 178).
Memang dibandingkan dengan sumber HTN lainnya seperti peraturan perundang-undangan, konvensi ketatanegaraan tidak memiliki kekuatan mengikat yang cukup kuat. Artinya, jika terjadi penolakan oleh pejabat negara dengan tidak lagi melaksanakannya, maka tidak ada sanksi apapun. Bahkan, pembangkangan terhadap konvensi tersebut dapat merubah konvensi/ kebiasaan ketatanegaraan yang telah ada.
Namun demikian, hadirnya konvensi ketatanegaraan sebagai salah satu sumber HTN menandakan bahwa peraturan tertulis saja tidak cukup untuk mengatur perilaku pejabat negara. Di luar itu, ada kebiasan-kebiasan baik (etika) yang mesti diperhatikan yang posisinya juga sama pentingnya dengan peraturan tertulis. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashidiqie dengan tegas menyatakan, baik the rule of law maupun the rule of ethics harus sama-sama menjadi pedoman bagi pejabat negara.
Kehadiran gubernur lama dalam acara pelantikan gubernur baru merupakan konvensi ketatanegaraan yang baik dan oleh karenanya perlu untuk terus dipertahankan karena hal ini dapat mendorong terciptanya kesinambungan atas program-program pemerintahan sebelumnya, menciptakan semangat persatuan dan kesatuan antar para pendukungnya masing-masing setelah sebelumnya dalam proses pilkada masyarakat terkondisikan dalam dua kubu yang saling berhadap-hadapan. Selain itu, sikap ini juga akan menjadi pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat bahwa kalah-menang dalam kontestasi pilkada adalah hal biasa.
[1] Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi FH UII. Kandidat Doktor FH UI Jakarta.